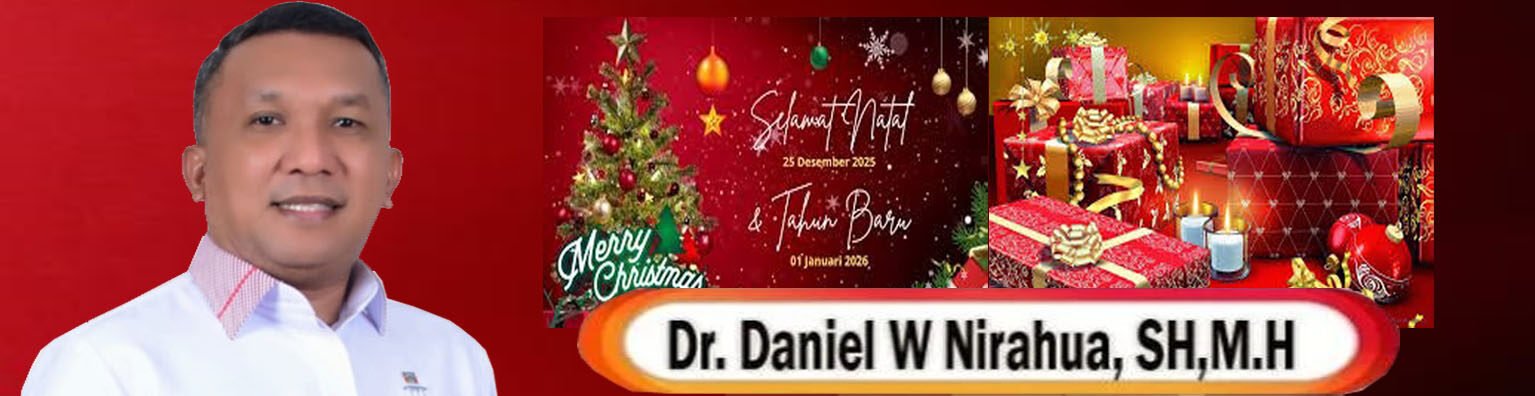Persoalan penutupan Gunung Botak sebenarnya bukan isu baru. Beberapa kali di masa pemerintahan Gubernur Maluku sebelumnya, wacana penutupan telah muncul, namun sering kali berakhir tanpa realisasi tegas karena tekanan sosial-politik, kepentingan ekonomi, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga. Baru pada masa pemerintahan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur HL–AV, keinginan tersebut kembali mencuat dengan komitmen yang jauh lebih serius dan strategis, bukan sekadar reaktif. Komitmen ini lahir dari kesadaran akan tanggung jawab moral dan konstitusional sebagai pemimpin daerah, yang menyaksikan secara langsung kompleksitas persoalan di Gunung Botak: mulai dari kerusakan ekologis akut, kriminalitas terorganisir dalam skema tambang ilegal, kemiskinan struktural, hingga konflik horizontal antarwarga dan masyarakat adat. Tambang yang awalnya dianggap sebagai jalan pintas kesejahteraan, justru berubah menjadi sumber kerentanan multidimensi.
Gubernur dan Wakilnya menyadari bahwa membiarkan situasi ini berlarut-larut bukan hanya kegagalan kebijakan, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi untuk melindungi rakyat dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penutupan Gunung Botak bukan semata tindakan administratif, tetapi manifestasi dari tanggung jawab etis—bahwa pemerintah hadir untuk menghentikan kehancuran dan membuka jalan baru menuju pemulihan.

Staf pengajar Universitas Islam Negeri AM Sangadji Ambon
Oleh: Fahmy Salatalohy
Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan HL–AV tengah merancang langkah-langkah transformasional: mulai dari audit lingkungan, rehabilitasi kawasan, perlindungan sosial bagi eks-penambang, hingga pembentukan forum dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga non-negara. Ini bukan hanya soal menutup akses fisik, tetapi membuka ruang kesadaran bersama bahwa sumber daya alam bukan untuk dieksploitasi tanpa batas, melainkan untuk diwariskan dalam keadaan lestari bagi generasi mendatang.
Top of Form
Bottom of Form
Lebih dari itu, langkah ini membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur pentahelix—yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat sipil, dan media—untuk membangun konsensus bersama mengenai model pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, transparan, dan berbasis kearifan lokal. Pemerintah tidak boleh bekerja sendiri; perlu ada desain kebijakan yang kolaboratif untuk merevitalisasi tata kelola pertambangan berbasis konservasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, dan penghormatan terhadap hak-hak adat. Penutupan ini harus dimaknai sebagai moratorium menuju transformasi tata kelola tambang rakyat yang legal, berkelanjutan, dan manusiawi. Peran para pemangku adat menjadi sangat penting untuk merumuskan kerangka etika pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya menjawab kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mewariskan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, keberanian Gubernur Hendrik Lewerissa dan wakilnya Abdullah Vanath tidak hanya mencerminkan sikap tegas terhadap pelanggaran hukum dan perusakan alam, tetapi juga menjadi simbol tanggung jawab moral dan politik yang lebih besar: membela hak hidup ekologis Maluku dan memutus rantai kapitalisasi ilegal atas tanah adat.
QUO VADIS MASYARAKAT ADAT
Dalih masyarakat adat untuk mempertahankan wilayahnya tentu tidak serta-merta diabaikan, sebab secara konstitusional dan historis, masyarakat adat memiliki hak atas tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Argumen ini sah dan kuat, apalagi jika disertai bukti kultural, genealogis, dan praktik-praktik adat yang mengatur kepemilikan serta pengelolaan wilayah. Namun, persoalan menjadi kompleks ketika wilayah adat tersebut digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan, melanggar hukum negara, serta menimbulkan konflik horizontal dan degradasi sosial.
Dalam konteks ini, penting dibedakan antara hak kepemilikan atas wilayah adat dengan hak untuk mengeksploitasi sumber daya di dalamnya tanpa batas. Pengakuan atas tanah adat bukanlah pembenaran untuk membiarkan aktivitas penambangan tanpa regulasi dan tanpa tanggung jawab ekologis. Dalam prinsip keadilan ekologis dan sustainable indigenous governance, hak adat selalu disertai dengan kewajiban untuk menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari kosmologi dan moralitas adat itu sendiri.
Gubernur Maluku dan Wakilnya dapat mengambil posisi sebagai penengah etik—bukan sebagai aktor represif—dengan membuka ruang dialog bersama dewan adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan otoritas lingkungan. Langkah ini bertujuan membentuk mekanisme bersama untuk memastikan bahwa perlindungan hak adat berjalan seiring dengan penyelamatan ekosistem Gunung Botak.
Solusi jangka panjang bisa diarahkan pada pendekatan co-management (pengelolaan bersama) antara pemerintah dan komunitas adat yang mengedepankan tiga prinsip: Legalitas formal, yaitu aktivitas tambang harus sesuai dengan hukum negara, etika ekologis, yaitu memastikan keseimbangan ekosistem tetap terjaga, Keadilan sosial, yaitu masyarakat adat dilibatkan secara aktif dan mendapat manfaat yang adil dan berkelanjutan dari pengelolaan wilayahnya.
Jika masyarakat adat benar-benar berniat mempertahankan wilayahnya, maka pertanyaan berikutnya adalah: apakah mereka bersedia mempertahankannya juga dari kerusakan dan kehancuran ekologis? Jika jawabannya ya, maka pemerintah dan masyarakat adat memiliki titik temu untuk bergerak bersama menyusun model tata kelola yang berbasis nilai-nilai adat, hukum negara, dan prinsip keberlanjutan yaitu komitmen untuk menjaga tanah, air, dan ekosistem sebagai warisan bersama yang tak ternilai.
Di titik inilah, dialog yang selama ini bersifat konfrontatif dapat beralih menjadi kolaboratif. Pemerintah dan masyarakat adat perlu duduk bersama untuk merumuskan model tata kelola baru—yang tidak hanya mengandalkan logika izin dan regulasi negara, tetapi juga mengakui, memulihkan, dan mengintegrasikan kearifan lokal sebagai sumber hukum ekologis. Dengan begitu, yang lahir bukan sekadar kebijakan teknokratik, melainkan perjanjian sosial-ekologis yang mengikat secara moral dan budaya. Model tata kelola ini harus berbasis tiga prinsip utama: 1. Legitimasi kultural dan hukum: Wilayah adat tetap diakui, tetapi pemanfaatannya tunduk pada batas-batas ekologis dan etika adat. Di sini, lembaga adat harus mereformulasi kembali nilai-nilai tradisional untuk menolak aktivitas eksploitasi yang merusak, sekaligus memperkuat peran pengawasan komunitas. 2. Ko-ekologi dan pengelolaan partisipatif: Pemerintah dan masyarakat adat bersama-sama menyusun sistem co-management, di mana masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki pengetahuan lokal, tanggung jawab moral, dan hak atas wilayahnya. 3.Keberlanjutan lintas generasi: Segala bentuk kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) menjadi kerangka normatif utama: jika suatu aktivitas berpotensi menimbulkan kerusakan permanen, maka pilihan yang bijak adalah menahan diri.
Dengan kerangka semacam ini, perjuangan masyarakat adat tidak lagi sekadar mempertahankan tanah dari intervensi luar, tetapi juga menegaskan posisi mereka sebagai penjaga kehidupan, bukan hanya pewaris lahan. Sementara pemerintah hadir bukan sebagai pemilik kuasa, melainkan sebagai fasilitator keadilan ekologis—yang menjamin bahwa setiap warga, adat maupun bukan, hidup dalam lingkungan yang sehat, lestari, dan bermartabat.
SETELAH DI TUTUP, APA LANGKAH SELANJUTNYA?
Setelah penutupan Gunung Botak dari aktivitas pertambangan ilegal, langkah-langkah strategis yang perlu diambil haruslah komprehensif, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang. Penutupan bukan akhir dari persoalan, melainkan awal dari proses pemulihan, rekonstruksi sosial-ekologis, dan transformasi tata kelola sumber daya alam. Berikut langkah-langkah lanjut yang disarankan:
- Rehabilitasi Ekosistem dan Audit Lingkungan
Langkah pertama adalah melakukan audit lingkungan secara menyeluruh untuk memetakan tingkat kerusakan akibat aktivitas tambang ilegal: pencemaran air dan tanah, kerusakan vegetasi, dan potensi longsor atau bencana ekologis. Hasil audit ini menjadi dasar untuk: rehabilitasi lahan dan reboisasi (penghijauan kembali), pembersihan sisa-sisa bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida, Restorasi kawasan hulu dan sempadan sungai
- Reintegrasi Sosial dan Ekonomi bagi Eks-Penambang
Penutupan tambang akan berdampak langsung terhadap mata pencaharian ribuan penambang lokal dan pendatang. Karena itu perlu disiapkan: Program alih profesi: pelatihan keterampilan (vocational training), pertanian organik, atau industri kreatif lokal, Skema bantuan sosial transisi: bantuan tunai sementara, subsidi pangan, dan jaminan sosial, pengembangan BUMDes atau koperasi desa untuk mengelola usaha ekonomi alternatif.
- Dialog dan Kesepakatan Bersama dengan Masyarakat Adat
Setelah ditutup, penting dilakukan musyawarah adat dan publik untuk merumuskan arah masa depan Gunung Botak. Langkah ini melibatkan: Dewan adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan pemuda, Penyusunan pakta bersama antara pemerintah dan masyarakat adat untuk melindungi Gunung Botak sebagai kawasan lindung atau kawasan kelola bersama, Pembentukan forum multipihak untuk monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
- Penegakan Hukum dan Rekonsiliasi Sosial
Penting ada penegakan hukum terhadap aktor-aktor utama perusak lingkungan (baik lokal maupun korporasi bayangan), namun dengan tetap mengedepankan: Prinsip restorative justice bagi pelanggar hukum yang bersifat ekonomi survival, mediasi dan rekonsiliasi antara kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya terlibat konflik horizontal, penertiban jalur distribusi bahan kimia tambang (merkuri/sianida) dari luar pulau.
- Transformasi Kebijakan: Menuju Tata Kelola Tambang Rakyat Legal dan Berkelanjutan
Pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan kebijakan menuju legalisasi dan pengelolaan tambang rakyat berbasis: zonasi ketat: wilayah yang boleh dan tidak boleh ditambang, Kepemilikan kolektif: tambang dikelola oleh koperasi adat atau BUMDes, Teknologi bersih dan ramah lingkungan, Sistem monitoring digital terhadap aktivitas tambang dan distribusi hasil tambang.
- Deklarasi Gunung Botak sebagai Kawasan Pengetahuan Adat dan Konservasi
Alternatif jangka panjang: menjadikan Gunung Botak sebagai kawasan konservasi berbasis adat dan pendidikan lingkungan. Ini dapat menjadi: Pusat penelitian agroekologi dan tambang hijau,
destinasi ekowisata edukatif, laboratorium sosial untuk praktik dialog antara ilmu pengetahuan modern dan pengetahuan lokal. Jika langkah-langkah di atas disusun dalam sebuah grand design recovery dan transformasi, maka penutupan Gunung Botak akan dikenang bukan sebagai tindakan koersif, melainkan sebagai momen balik (turning point) menuju keadilan ekologis dan kedaulatan masyarakat lokal.
KEBIJAKAN GUBERNUR TERHADAP KORPORASI?
Pertanyaan ini sangat krusial karena menyangkut relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat adat/lokal. Dalam konteks Gunung Botak, kebijakan Gubernur Maluku terhadap korporasi yang terlibat (secara langsung maupun tidak langsung) dalam aktivitas pertambangan harus tegas, transparan, dan berlandaskan hukum serta moral ekologis. Berikut ini analisis dan arah kebijakan yang semestinya atau idealnya diambil Gubernur terhadap korporasi di Gunung Botak:
- Audit Legalitas dan Jejak Keterlibatan Korporasi
Langkah pertama yang harus diambil oleh Gubernur adalah memerintahkan audit investigatif independen terhadap seluruh korporasi yang pernah atau sedang beroperasi di sekitar Gunung Botak. Audit ini mencakup: legalitas izin usaha pertambangan (IUP), termasuk proses perolehannya, Jejak keterlibatan korporasi dalam skema penambangan ilegal (misalnya melalui penyediaan alat berat, bahan kimia, atau pembelian hasil tambang ilegal), Dugaan pelanggaran AMDAL dan pencemaran lingkungan. Kebijakan konkret: jika ditemukan pelanggaran, maka IUP harus dicabut dan diproses hukum sesuai UU Minerba, UU Lingkungan Hidup.
- Moratorium dan Peninjauan Kembali Seluruh Izin Korporasi
Gubernur memiliki kewenangan administratif untuk: menghentikan sementara semua aktivitas korporasi tambang di wilayah Gunung Botak dan sekitarnya melalui moratorium regional, Melakukan peninjauan kembali (review) seluruh izin eksplorasi dan eksploitasi tambang yang dikeluarkan pemerintah sebelumnya Ini menjadi bagian dari proses transformasi menuju tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan, serta memulihkan kembali kepercayaan publik.
- Pelarangan Intervensi Ekonomi Korporasi dalam Konflik Horizontal
Dalam banyak kasus, korporasi masuk ke wilayah konflik masyarakat (adat vs pendatang vs penambang lokal) dengan memainkan peran sebagai sponsor informal. Gubernur harus melarang dan mengecam keras bentuk-bentuk intervensi ekonomi yang: menyuap tokoh lokal, menyediakan logistik untuk aktivitas illegal, membiayai kekerasan atau konflik horizontal terselubung. Kebijakan yang perlu dibuat: Perda atau Pergub tentang Korporasi Bertanggung Jawab Sosial-Ekologis (CSR wajib + keterlibatan masyarakat adat).
- Mendorong Korporasi Bertanggung Jawab dalam Pemulihan Lingkungan.
Jika ada korporasi yang terbukti melakukan eksploitasi tanpa tanggung jawab, maka Gubernur dapat menuntut mereka secara administratif dan hukum untuk membiayai pemulihan lingkungan (ecological restoration). Ini sesuai prinsip “polluters pay” dalam hukum lingkungan: pelaku kerusakan bertanggung jawab membayar biaya rehabilitasi.
- Mengganti Model Kontrak Eksploitatif dengan Model Kolaboratif
Jika masih diperlukan kerja sama dengan entitas bisnis, maka bukan model korporasi besar yang eksploitatif yang harus diberi ruang, melainkan: Koperasi tambang rakyat, BUMDesa atau perusahaan daerah berbasis masyarakat lokal, skema Public-Private-People Partnership (PPPP) berbasis nilai ekologis dan adat. Gubernur perlu menyusun Blueprint tata kelola tambang rakyat yang menolak skema konsesi besar yang merugikan rakyat.
- Mengawal Netralitas Aparat dan Birokrasi dari Tekanan Korporasi
Gubernur harus menjamin: tidak ada tekanan kepada dinas ESDM, lingkungan hidup, atau aparat keamanan, Proses perizinan dan pengawasan dilakukan secara digital dan transparan termasuk membuka kanal pengaduan publik terhadap penyimpangan atau praktik manipulatif korporasi. Kebijakan Gubernur terhadap korporasi di Gunung Botak harus berpijak pada keberpihakan terhadap rakyat, keberlanjutan ekologi, dan supremasi hukum. Dalam jangka panjang, penolakan terhadap korporasi eksploitatif harus disertai dengan penataan ulang sistem ekonomi lokal agar masyarakat tidak tergantung pada tambang ilegal atau korporasi besar yang merampas tanah dan merusak lingkungan.
Semoga penutupan Gunung Botak tidak hanya menjadi akhir dari praktik eksploitasi dan kerusakan lingkungan, tetapi juga menjadi awal dari kesadaran kolektif untuk membangun masa depan Maluku yang berkeadilan ekologis, bermartabat secara budaya, dan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. (*)