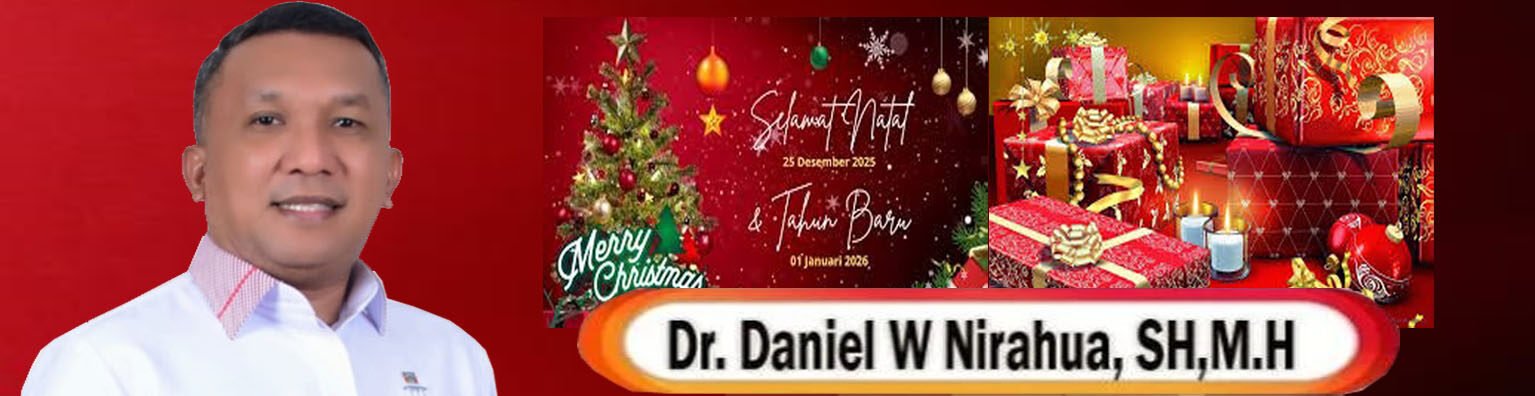Dalam khazanah filsafat politik klasik, negara tidak pernah dimaknai semata-mata sebagai alat
kekuasaan, melainkan res publica—sebuah “urusan bersama” yang bertumpu pada keadilan, hukum
yang tertib, dan kebajikan moral warganya. Bagi saya, ide ini menegaskan bahwa negara sejati
hanya bisa berdiri kokoh jika dijaga oleh warga yang sadar akan tanggung jawabnya, serta dipimpin
oleh orang-orang yang berkeutamaan dan memiliki nurani publik. Dengan begitu, republik bukan
sekadar struktur politik, melainkan perwujudan kontrak moral yang berkelanjutan antar warga.
Saya melihat bahwa kita hari ini hidup dalam konstruksi yang secara formal masih menyebut
dirinya republik, tetapi secara substansi semakin menjauh dari makna res publica itu sendiri.
Berbagai regulasi lahir silih berganti, lembaga baru dibentuk, tetapi fondasi etikanya justru rapuh.
Hukum kerap tajam ke bawah dan tumpul ke atas, keadilan kerap menjadi komoditas tawar-
menawar, dan jabatan publik menjelma sekadar jalur transaksi kepentingan.
Sejarah membuktikan bahwa hukum tanpa moralitas hanya akan menjadi instrumen yang dingin,
kehilangan ruh keadilan yang seharusnya ia tegakkan. Saya percaya, di titik inilah letak penyakit
kita. Kita tidak kekurangan aturan, tetapi miskin teladan. Kita tidak kekurangan pejabat, tetapi
sering kekurangan negarawan. Politik kehilangan nilai pengabdian, bergeser menjadi panggung
kepentingan pribadi dan simbol gengsi. Sementara itu, kejujuran, kesederhanaan, dan integritas
lebih sering menjadi slogan ketimbang realitas.
Yang lebih mengkhawatirkan, krisis etika ini tidak hanya menjalar di lingkar elite, tetapi juga
menular ke kewargaan. Saya menyaksikan bagaimana ruang publik perlahan kehilangan denyutnya.
Keterlibatan rakyat dalam politik direduksi menjadi ritual lima tahunan di bilik suara, selebihnya
tenggelam di bawah hiruk-pikuk populisme, arus disinformasi, dan dominasi kepentingan modal.
Padahal, republik lahir dari cita-cita besar agar rakyat terlibat penuh sebagai pemilik negara.
Sayangnya, cita-cita itu kian kabur ditelan pragmatisme.
Lebih jauh lagi, yang berbahaya adalah saat warga negara mulai kehilangan rasa memiliki. Ketika
rakyat merasa urusan negara adalah milik segelintir elite, maka di situlah republik mulai berubah
menjadi ruang privat, bukan lagi urusan bersama. Institusi yang seharusnya melayani publik
berubah menjadi benteng kepentingan kelompok. Dalam keadaan seperti ini, krisis tidak lagi
sekadar politik, melainkan eksistensial: republik hanya tinggal nama, hukum tinggal teks, moral
publik lenyap tanpa bekas.
Saya meyakini bahwa penyembuhnya bukan semata-mata reformasi kelembagaan, melainkan
kebangkitan etika publik. Kewargaan harus dirawat agar tak berubah menjadi peran pasif. Kita
perlu menanamkan kembali gagasan bahwa menjadi warga negara berarti memikul tanggung jawab
moral, bukan sekadar menuntut hak. Kita perlu mendesak agar para pemimpin memiliki pondasi
nurani, bukan sekadar kepiawaian retorika. Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam lingkaran
berbahaya di mana negara lahir dari idealisme tetapi runtuh oleh pengkhianatan terhadap nilai-nilainya sendiri.

Oleh : M. Akhwandany Uar.
Mahasiswa Fak. Hukum.
Universitas Muhammadyah Yogjakarta
Lebih lanjut lagi krisis etika bernegara juga menuntut kita untuk bercermin pada pendidikan
kewargaan yang kita jalankan. Saya melihat, di ruang kelas kita, pelajaran tentang Pancasila,
konstitusi, atau tata negara sering hanya menjadi hafalan teks tanpa dialektika kritis. Nilai-nilai
luhur yang diajarkan berhenti di kertas ujian, tidak menetes menjadi laku sehari-hari. Padahal,
pembentukan karakter warga negara sejati dimulai dari bangku sekolah. Jika generasi muda hanya
dijejali jargon, tanpa dibiasakan berpikir kritis, maka cita-cita republik akan terus terombang-
ambing di tangan generasi yang rapuh secara moral.
Selain itu, penting bagi kita untuk menyoroti peran media massa dan ruang digital yang kini
menjadi arena baru politik kewargaan. Alih-alih menjadi ruang diskusi yang mencerahkan, media
sosial sering kali berubah menjadi panggung kebencian, fitnah, dan penggiringan opini. Saya
percaya, warga negara di era digital harus lebih berdaya: bukan hanya sebagai konsumen informasi,
tetapi juga sebagai penjaga kewarasan publik. Membaca ulang republik berarti juga membaca ulang
bagaimana teknologi bisa menjadi jembatan etika publik, bukan sekadar alat propaganda kekuasaan.
Tak kalah penting, saya ingin menekankan peran komunitas akar rumput—organisasi masyarakat
sipil, kelompok diskusi, forum keagamaan—yang memiliki potensi besar menjadi benteng nilai
bersama. Dalam sejarahnya, republik lahir bukan hanya dari elite, tetapi juga dari gerakan rakyat.
Kita membutuhkan ruang-ruang alternatif di mana warga bisa saling mendidik, saling
mengingatkan, dan saling mengorganisir untuk memperjuangkan nilai keadilan dan kebajikan.
Ruang-ruang inilah yang dapat menghidupkan kembali semangat gotong royong, salah satu ciri asli
bangsa kita.
Saya juga percaya bahwa pembangunan etika publik tidak bisa berdiri sendiri tanpa teladan nyata di
tingkat elite. Sehebat apapun pendidikan kewargaan, sehebat apapun diskursus di ruang publik,
semua akan sia-sia jika pemimpin tidak menunjukkan integritas. Oleh sebab itu, reformasi etika
harus dimulai dari puncak piramida: pemimpin yang tulus mengabdi, transparan dalam tindakan,
dan rela dikritik. Teladan ini akan menetes ke bawah, mengalir ke birokrasi, lalu merembes ke
masyarakat. Itulah mengapa saya berkeyakinan, regenerasi politik harus terus didorong agar ruang
kekuasaan tidak selalu dihuni wajah lama dengan logika lama.
Dalam keadaan sekarang, tugas kita bukan sekadar mengkritik, tetapi membangun ulang kultur
bernegara yang bermoral. Kita perlu mengembalikan makna republik sebagai res publica—urusan
bersama, milik bersama, dan tanggung jawab bersama. Sebab jika kita terus membiarkan hukum
diperdagangkan, etika publik terkikis, dan rakyat dibisukan, maka kita sedang mempercepat
kemunduran bangsa.
Tulisan ini sebagai seruan moral saya untuk membangkitkan kembali nurani publik. Negeri ini tidak
akan berubah hanya dengan mengganti pemimpin, tetapi dengan memperbarui cara kita memaknai
kewargaan. Republik Indonesia hanya akan selamat jika dijaga oleh warga yang peduli dan
pemimpin yang bermoral. Itulah satu-satunya jalan agar kita tidak sekadar memiliki republik di atas
kertas, tetapi benar-benar hidup dalam cita-cita kebersamaan dan keadilan yang nyata, seperti yang dicita citakan oleh bapak pendiri bangsa.