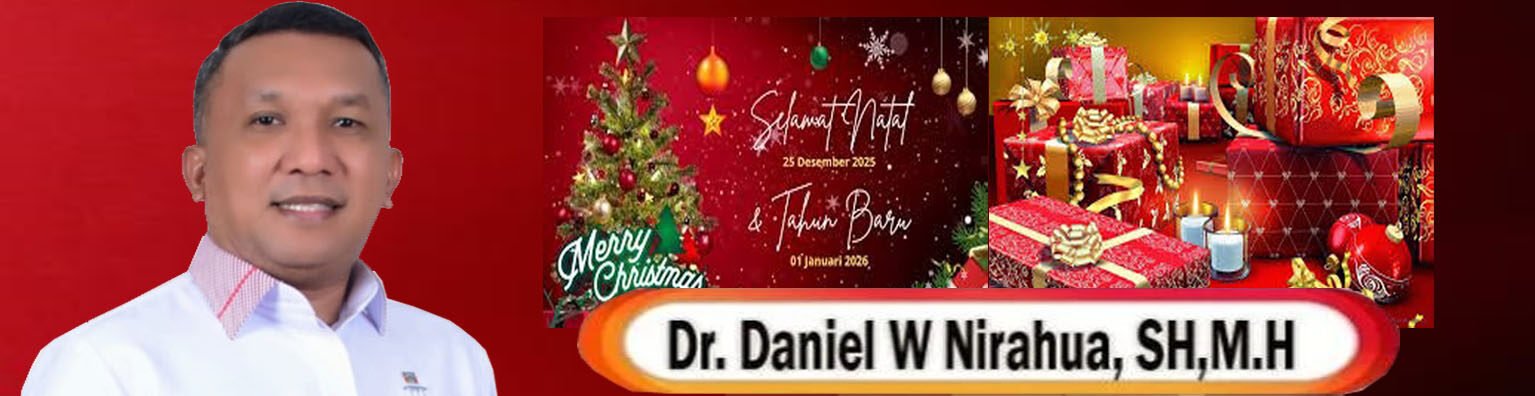MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA— Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto sebagai langkah yang mengkhianati semangat Reformasi 1998 serta bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Dalam pernyataannya hari ini, Hendardi menyoroti sikap Menteri Kebudayaan RI, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, karena menyebut seluruh tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial — termasuk Soeharto — telah memenuhi kriteria penerima gelar pahlawan nasional.
Menurut Hendardi, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama elit politik di sekitarnya untuk memutihkan sejarah kelam Orde Baru dan mengangkat kembali figur Soeharto sebagai simbol negara.
“Setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden, MPR bahkan mencabut Pasal dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 yang secara tegas menyebut nama Soeharto. Itu adalah sinyal awal dari penghapusan tanggung jawab sejarah terhadap pelanggaran HAM, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan selama 32 tahun pemerintahannya,” ujar Hendardi.
Ia menegaskan bahwa pencabutan TAP MPR tersebut adalah langkah yang salah dan berbahaya, karena menghapus memori kolektif bangsa terhadap akar lahirnya gerakan Reformasi 1998.
“Mereka yang mendorong pencabutan itu sedang mengalami amnesia politik dan sejarah. Ini bukan hanya pengkhianatan terhadap reformasi, tapi juga pengkhianatan terhadap nurani bangsa,” tegasnya.
Hendardi juga menyoroti aspek hukum positif yang seharusnya menjadi acuan Dewan Gelar. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, penerima gelar pahlawan nasional harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain memiliki integritas moral, keteladanan, berkelakuan baik, serta tidak pernah dipidana minimal lima tahun penjara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
“Fakta hukum menyebut sebaliknya,” kata Hendardi.
Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan No. 140 PK/Pdt/2005 telah menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kewajiban membayar lebih dari Rp 4,4 triliun kepada negara.
Selain itu, berbagai pelanggaran HAM berat dan praktik otoritarianisme selama masa pemerintahan Soeharto — meski belum diuji di pengadilan — merupakan catatan kelam yang tak dapat dihapus dari sejarah bangsa.
“Dengan semua catatan itu, menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah tindakan melawan hukum, logika moral, dan akal sehat publik. Jika Presiden tetap memaksakan, maka publik berhak menilai bahwa absolutisme kekuasaan sedang diterapkan kembali,” ujar Hendardi.
Ia bahkan menutup pernyataannya dengan peringatan keras:
“Jika gelar itu benar-benar disahkan, maka sejarah akan mencatat bahwa pemerintah hari ini telah mengulang kesalahan masa lalu — menghidupkan kembali semangat L’État, c’est moi — Negara adalah aku.”
Langkah pemerintah dalam mengusulkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional kini memicu gelombang kritik tajam dari masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat HAM di seluruh Indonesia. Mereka menilai keputusan itu tidak hanya melukai hati korban rezim Orde Baru, tetapi juga mencederai cita-cita Reformasi 1998 yang lahir dari darah dan air mata rakyat. (MIM-MDO)