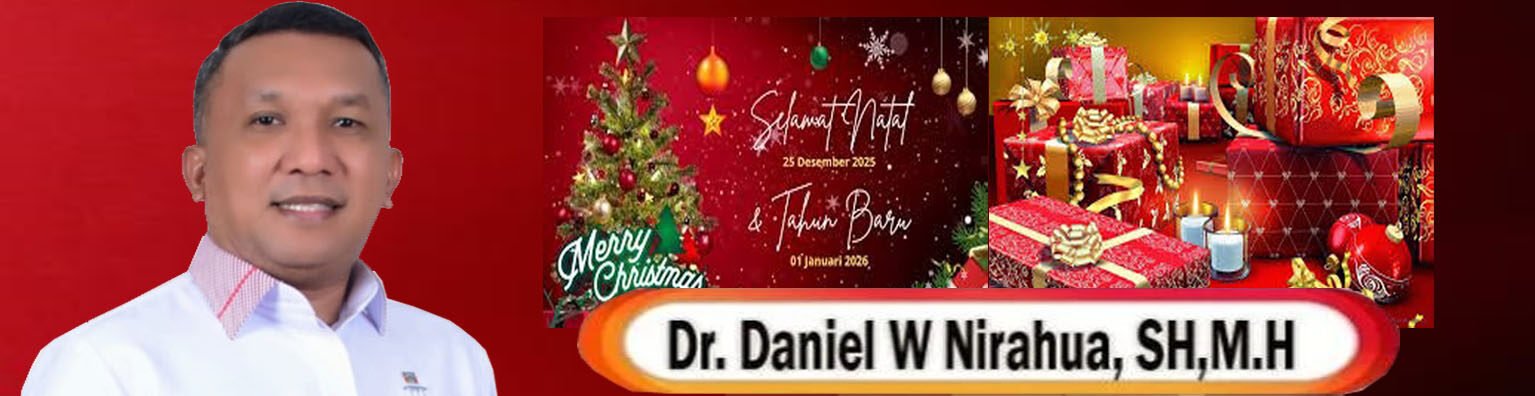Penanganan kritik publik terhadap pejabat negara kembali menuai sorotan serius. Kritik yang seharusnya menjadi bagian dari kontrol demokratis, kini berpotensi diseret ke ranah pidana, bertentangan dengan semangat KUHP Baru yang menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau jalan terakhir.
Hal ini mengemuka menyusul polemik pelaporan warga terhadap kepala daerah terkait dugaan pengelolaan retribusi tambang ilegal. Kritik yang disampaikan melalui selebaran dengan frasa “diduga ilegal” justru dilaporkan ke aparat penegak hukum, memicu kekhawatiran atas menguatnya praktik kriminalisasi ekspresi publik.
Dalam negara hukum demokratis, kritik terhadap pejabat publik bukanlah penyimpangan, melainkan kebutuhan. Pejabat negara, termasuk kepala daerah, memegang mandat publik sehingga harus siap menerima standar kritik yang lebih tinggi dibanding warga biasa. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
KUHP Baru: Hukum Pidana Bukan Alat Membungkam
KUHP Baru menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan jika unsur delik terpenuhi secara ketat. Delik pencemaran nama baik sendiri ditempatkan sebagai delik aduan absolut, yang menuntut kehati-hatian ekstra dalam penerapannya.
Penggunaan frasa “diduga” menunjukkan bahwa kritik tersebut belum merupakan klaim kebenaran final, melainkan ekspresi dugaan dalam ruang kepentingan publik. Dalam perspektif hukum pidana modern, pernyataan semacam ini tidak serta-merta dapat dipidana tanpa pembuktian adanya niat menyerang kehormatan pribadi secara faktual dan pasti.
Penggunaan hukum pidana secara reaktif terhadap kritik publik justru berisiko menimbulkan chilling effect, yakni ketakutan masyarakat untuk bersuara. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan sendi-sendi demokrasi dan partisipasi warga negara.
Perspektif Teori Hukum
Pemikiran Gustav Radbruch menempatkan hukum pada tiga nilai utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Jika kepastian hukum digunakan tanpa mempertimbangkan keadilan dan manfaat sosial, hukum kehilangan legitimasi moralnya.
Sementara Ronald Dworkin menegaskan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan mekanis, melainkan sistem prinsip yang harus melindungi hak-hak fundamental, termasuk kebebasan berekspresi.
Dalam konteks pengawasan kekuasaan, kebebasan berpendapat tidak boleh dikalahkan oleh tafsir legalistik yang sempit.
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief, yang menekankan bahwa hukum pidana harus digunakan secara selektif dan berorientasi pada tujuan sosial, bukan sebagai alat pembalasan atau pembungkaman.
Hukum sebagai Penyeimbang
Dari sisi lain, pelaporan warga juga dapat dipahami sebagai upaya melindungi kehormatan pribadi. Namun, dua kepentingan yang sama-sama sah ini tidak harus diselesaikan melalui konfrontasi pidana.
Pendekatan yang lebih proporsional adalah mendorong klarifikasi terbuka, mekanisme pengawasan yang objektif, serta penggunaan jalur pidana secara hati-hati dan terbatas. Dalam negara hukum yang sehat, hukum pidana bukan senjata politik, melainkan penjaga etika kekuasaan dan kebebasan warga negara.
Tantangan utama penegakan hukum hari ini bukan memilih berpihak pada siapa, melainkan memastikan hukum bekerja sebagai penyeimbang antara kekuasaan dan kebebasan. Di situlah hukum diuji, bukan hanya sebagai kumpulan pasal, tetapi sebagai fondasi demokrasi (***)