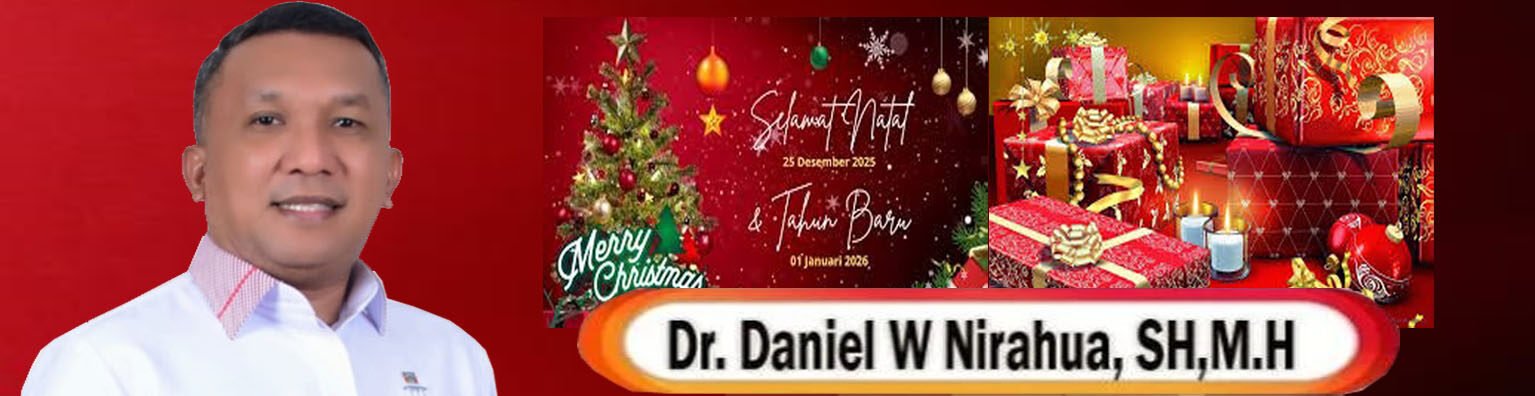MALUKU INDOMEDIA.COM, Ambon– Gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 memperlihatkan rapuhnya relasi negara dan rakyat. Tragedi yang menewaskan sejumlah orang, termasuk pengemudi ojek online Affan Kurniawan, menjadi simbol krisis legitimasi negara hukum. Aksi ini tidak sekadar protes atas kebijakan DPR yang memberikan tunjangan perumahan Rp50 juta bagi anggotanya, tetapi juga akumulasi kekecewaan rakyat terhadap ketidakadilan ekonomi, lemahnya representasi politik, dan rapuhnya penegakan hukum.
Kebijakan DPR yang dianggap elitis menyinggung rasa keadilan publik. Alih-alih lahir dari komunikasi demokratis yang deliberatif, keputusan tersebut justru menampakkan elite capture — kebijakan untuk kepentingan segelintir elit, bukan rakyat. Ketidakadilan distribusi inilah yang kemudian menyulut kemarahan sosial.
Tragedi kian membesar ketika aparat keamanan menggunakan pendekatan represif. Kematian Affan Kurniawan menjadi luka bersama, mencerminkan wajah negara yang gagal melindungi warganya. Hal ini mengingatkan kita pada deretan tragedi serupa: 1998, 2019, hingga 2020. Semua menunjukkan pola berulang: negara gagal membaca aspirasi publik dan justru membungkam dengan kekerasan.
 Oleh: Achmad Fikri Hehanussa, Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia
Oleh: Achmad Fikri Hehanussa, Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia
Eskalasi demonstrasi yang meluas di berbagai kota, termasuk pembakaran gedung DPRD Makassar, menunjukkan bahwa ini bukan sekadar protes spontan. Ada akar yang lebih dalam: krisis keadilan, narasi ketidakadilan ekonomi, serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap institusi politik.
Krisis pun merambah ke dimensi ekonomi: IHSG anjlok, rupiah melemah, transportasi publik lumpuh, bisnis terguncang. Stabilitas politik yang rapuh berimbas pada ketidakpastian ekonomi. Padahal menurut Pasal 33 UUD 1945, negara seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat. Ironisnya, negara justru memperlihatkan kegagalan dalam memberi rasa aman sosial-ekonomi masyarakat.
Tragedi ini juga menguji makna sejati negara hukum. Hukum tidak boleh sekadar prosedural, tetapi harus sahih secara moral dan sosial. Jika hukum digunakan hanya untuk melindungi elit dan mengorbankan rakyat, maka negara telah kehilangan makna sejatinya sebagai negara hukum yang adil.
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membaca krisis ini bukan sebagai ancaman keamanan, tetapi sebagai sinyal korektif. Jalan keluar tidak bisa lagi ditempuh dengan represi, melainkan reformasi: mengembalikan legitimasi melalui kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, mereformasi aparat penegak hukum, dan membangun kembali kepercayaan publik dengan langkah nyata, bukan retorika.
Tragedi ini menjadi cermin bagi Indonesia. Apakah bangsa ini setia pada janji konstitusi untuk menjadi negara hukum yang menjunjung keadilan sosial, atau terus terjebak dalam lingkaran kekerasan, ketidakadilan, dan krisis legitimasi? Jika gagal mengambil pelajaran, luka sosial akan terus membesar, dan demokrasi konstitusional Indonesia akan kehilangan makna sejatinya. (REDAKSI)