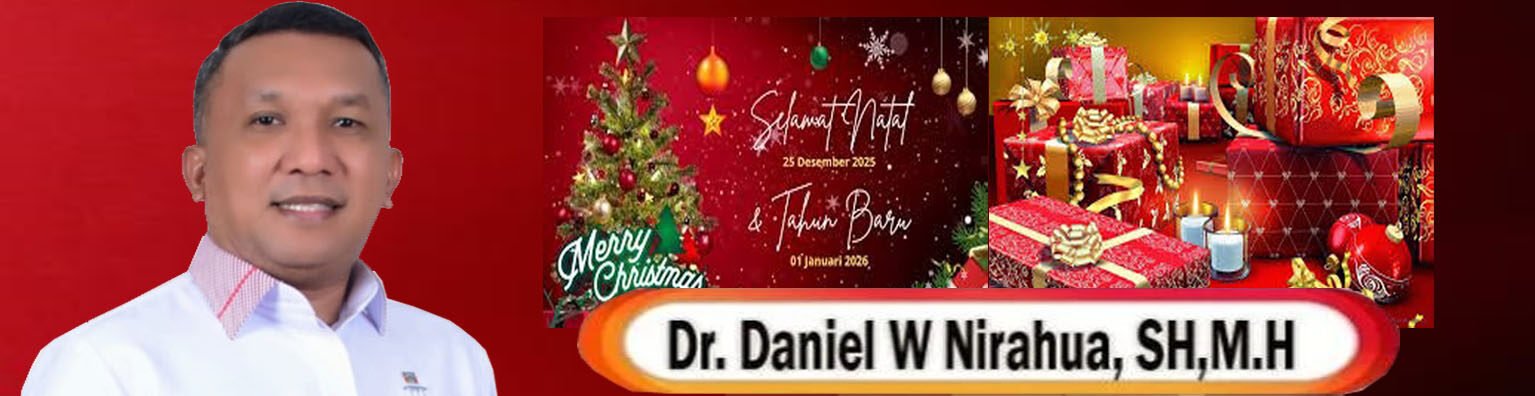BUMD di Maluku sedang sakit — bukan karena cuaca atau faktor eksternal semata, tetapi karena penyakit kronis yang berakar pada praktik pengelolaan yang abai pada prinsip tata kelola baik, transparansi, dan profesionalisme. Bila pemerintah daerah Maluku membiarkan kondisi ini berlarut, publik yang menanggung beban akhirnya bukan perusahaan saja, melainkan pelayanan publik dan APBD yang tergerus.
Di provinsi kita ada tiga BUMD besar yang mestinya menjadi motor pembangunan: Bank Maluku, PT Dok Waiame, dan PD Panca Karya. Ironisnya, ketiganya sedang bermasalah: Kejaksaan Negeri Ambon memeriksa kasus korupsi pengadaan seragam di Bank Maluku; PT Dok Waiame terseret kasus korupsi yang juga ditangani Kejari Ambon; bahkan PD Panca Karya ikut terjerat imbas salah kelola di Dok Waiame. Ini bukan sekadar headline — ini alarm.
Masalah ini bukan fenomena baru. Sejak lama BUMD-BUMD di Maluku menunjukkan pola yang sama: manajemen yang berjalan menurut selera penguasa, keputusan strategis yang dipengaruhi kepentingan politik sesaat, dan pengawasan yang lemah. Dalam bahasa sehari-hari: pengelolaan “asal bapak senang” yang merusak fungsi ekonomi perusahaan daerah.
Ambil contoh Bank Maluku. Meski ada laporan bahwa cabang di Maluku Utara menunjukkan kinerja profit, laba semata tidak menutupi borok tata kelola yang ada. Bahkan upaya korporatisasi atau penggabungan (seperti bergabungnya Bank Maluku dengan Bank DKI Jakarta) tidak otomatis menyelesaikan masalah bila akar tata kelolanya dibiarkan bertahan.
Sementara itu, Dok Waiame dan PD Panca Karya menggambarkan risiko ketika BUMD menjalankan bisnis tanpa kontrol yang ketat: satu kasus korupsi bisa menyeret beberapa entitas sekaligus, menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang sulit dipulihkan. Dampaknya berantai: proyek tertunda, kredit macet, pendapatan daerah menurun.
Konsekuensinya jelas: pendapatan asli daerah yang potensial berkurang, kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset daerah menipis, dan modal sosial untuk pembangunan melemah. Jika dibiarkan, BUMD yang mestinya menjadi alat pembangunan malah menjadi beban fiskal dan politis.

DARUL KUTNI TUHEPALY
(MANTAN ANGGOTA DPRD MALUKU)
Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama: perbaikan tata kelola (good corporate governance) harus ditempatkan sebagai prioritas non-negosiasi. Dewan pengawas dan direksi harus disusun melalui seleksi terbuka, menyertakan kompetensi profesional, keterwakilan independen, dan kriteria integritas yang ketat — bukan sekadar hadiah bagi kroni politik.
Kedua: profesionalisasi manajemen. Kepala perusahaan dan jajaran eksekutif harus direkrut memakai mekanisme kompetitif, kontrak kinerja jelas, KPI terukur, dan mekanisme evaluasi berkala yang transparan. Kontrak manajemen dengan insentif dan sanksi finansial membuat akuntabilitas lebih nyata.
Ketiga: reformasi pengendalian internal. Audit internal yang kuat, audit eksternal independen yang rutin, penerapan e-procurement, dan sistem pelaporan keuangan terpadu wajib diberlakukan. Semua proses pengadaan dan transaksi harus dapat diaudit secara elektronik untuk memangkas celah korupsi.
Keempat: langkah antikorupsi konkret. Proteksi bagi whistleblower, saluran pengaduan yang aman, dan kerja sama proaktif dengan aparat penegak hukum ketika ditemukan indikasi penyimpangan. Upaya penelusuran aset dan pemulihan kerugian harus menjadi prioritas untuk memulihkan dana publik.
Kelima: restrukturisasi strategis bisnis BUMD. Pemerintah daerah harus menyusun rencana bisnis jangka menengah — mengidentifikasi core business, menyingkirkan unit yang tidak kompetitif, atau mencari mitra swasta melalui skema BUMD bila diperlukan. Privatisasi parsial atau pengalihan fungsi juga bisa dipertimbangkan jika itu solusi paling rasional secara ekonomi.
Keenam: penguatan kapasitas dan budaya perusahaan. Pelatihan manajemen, pembentukan kode etik yang dipatuhi seluruh pegawai, rotasi fungsi untuk mencegah oligarki internal, serta penegakan budaya meritokrasi adalah investasi jangka panjang yang harus dijalankan.
Ketujuh: pengaturan regulasi dan pengawasan legislatif. DPRD dan perangkat pengawas daerah harus lebih proaktif: menuntut laporan rutin, memanggil direksi saat terjadi penyimpangan, dan menerapkan mekanisme sanksi administratif yang tegas — termasuk pembekuan anggaran atau penggantian pengurus ketika diperlukan.
Akhirnya, transparansi kepada publik menjadi kunci. Laporan keuangan BUMD, rencana bisnis, hasil audit, dan perkembangan penanganan kasus korupsi harus dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Ketika warga dapat mengawasi, ruang untuk praktik gelap otomatis menyempit.
Perbaikan BUMD Maluku bukan tugas teknis semata; ia soal keberanian politik untuk menyingkirkan kepentingan jangka pendek, serta komitmen jangka panjang membangun institusi yang sehat. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama, bukan saling lempar tanggung jawab.
Jika langkah-langkah ini dijalankan dengan serius, BUMD bisa kembali menjadi mesin penggerak ekonomi daerah: menyumbang PAD yang stabil, menyediakan layanan publik lebih baik, dan membuka ruang untuk investasi yang berkelanjutan. Tetapi jika dibiarkan, kita hanya akan menyaksikan aset publik terus menyusut oleh praktik-praktik yang merugikan rakyat.
Waktunya bertindak sekarang — karena setiap hari keterlambatan berarti potensi pendapatan dan kepercayaan yang hilang. BUMD sehat bukan kemewahan birokratis, melainkan prasyarat bagi pembangunan Maluku yang adil dan sejahtera. (***)